Surakarta, 2 Juli 2025. Di tengah urbanisasi yang kian masif dan krisis global yang terus menghantui sektor pangan, sekelompok mahasiswa Sastra Arab Universitas Sebelas Maret (UNS) menawarkan pendekatan tak biasa dengan menjembatani teks hadis dengan strategi ketahanan pangan modern. Ketahanan pangan adalah isu lama dengan wajah baru yang kemudian digagas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Swasembada dalam Sabda” yang digelar di Solo Technopark (2/7), sebagai bagian dari program riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diketuai oleh Adam Fakhriza Albarru.
FGD ini menjadi ruang pertemuan yang jarang terjadi antara pakar linguistik, pakar hukum Islam, birokrat pangan, mahasiswa, dan publik. “Dalam bahasa Arab itu kan petani disebut dengan fallāḥ sama kaya petikan kata pada ḥayya ‘alal-falāḥ. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian bisa membuka celah-celah penelitian baru, misalnya dengan mempelajari pola susunan katanya kemudian meneliti ada keterikatan makna seperti apa sehingga kedua kata tersebut memiliki struktur huruf yang hampir sama.” ujar Dr. Muhammad Ridwan S.S., M.A., unruk membuka diskusi dengan menggarisbawahi keterkaitan makna dalam bahasa Arab antara fallāḥ (petani) dan falāḥ (keberhasilan) sebuah permainan akar kata yang menunjukkan adanya keterikatan makna antara pertanian dan keberhasilan yang saking pentingnya sampai diserukan 5 kali dalam sehari dalam panggilan ibadah umat Islam.
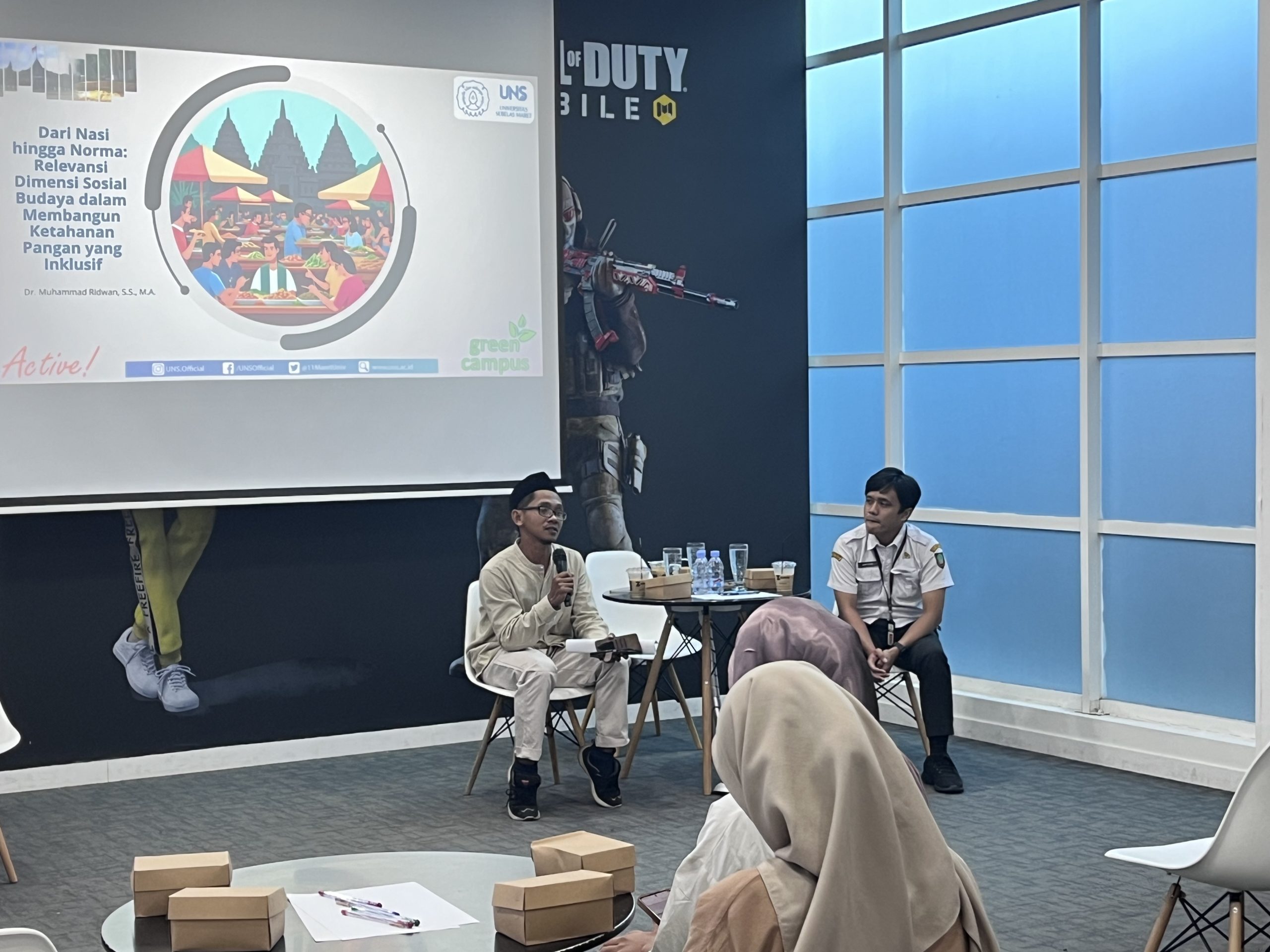
Pada sesi berikutnya, Bayu Windiharto Putro, S.E., Penelaah Teknis Kebijakan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, menjabarkan realitas yang jauh lebih konkret. Ia mengungkapkan bahwa luas lahan sawah di Surakarta menyusut dari tahun ke tahun, dan lebih buruknya lagi, tidak ada satupun kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang secara eksplisit dilindungi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 2021–2041. Namun, itu bukan berarti tidak ada harapan. Pemerintah kota tetap mengupayakan berbagai strategi adaptif seperti urban farming, pengembangan kelompok tani perkotaan, serta penyuluhan produktivitas dan bantuan alat mesin pertanian. Ini bukti bahwa ketahanan pangan bisa dibangun dimanapun lewat inovasi berbasis komunitas dan efisiensi, bukan sekadar luasan lahan.
Namun begitu, kita tahu bahwa ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan dengan teknologi atau kebijakan semata. Di tengah masyarakat yang mayoritas memeluk Islam, pendekatan teologis bisa berpeluang membuka jalur pemahaman yang lebih kuat. Nilai-nilai spiritual yang menyertai proses menanam, mengolah, dan membagikan pangan bisa menjadi jembatan antara program negara dan kesadaran masyarakat. Kemandirian pangan tidak harus dimulai dari lumbung negara, tapi bisa dari pot bunga di teras rumah. Maka pertanyaannya: bagaimana membumikan gagasan ini dalam bahasa yang bisa menyentuh kesadaran masyarakat?
Di titik inilah mahasiswa Sastra Arab turut mengambil peran. Tidak dengan sketsa kebijakan atau peta distribusi logistik, tapi dengan teks-teks hadis yang mereka pelajari lantas diolah kembali sehingga memunculkan pertanyaan: bagaimana keyakinan spiritual yang diklaim sebagai raḥmatan lil-ī’ālamīn memandang pangan, pertanian, dan distribusi hasil panen? Dan bagaimana semua itu bisa diterjemahkan ke dalam konteks hari ini, ketika pangan jadi persoalan nasional?

Perlu dipahami bahwa Sastra Arab sebagai bidang kajian tidak secara langsung mempelajari agama Islam. Namun karena bahasa Arab merupakan medium utama dalam penyebaran ajaran Islam dan karena banyak teks keagamaan, termasuk hadis, ditulis dalam bahasa Arab maka keterhubungan itu tak terhindarkan. Apalagi, wilayah Arab pernah menjadi pusat keilmuan dan peradaban Islam selama berabad-abad. Maka Sastra Arab kerap bersentuhan dengan teks keagamaan bukan dalam rangka menjalankan tafsir teologis, melainkan untuk menelaahnya secara linguistik, filologis, dan kontekstual. Pendekatan inilah yang membuka kemungkinan untuk membaca ulang sabda Nabi dengan kacamata sosial, ekologis, bahkan politis tanpa kehilangan kepekaan maknanya.
Salah satu narasumber, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, S.H., M.H., M.A. pakar hukum Islam sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam UIN Raden Mas Said menyampaikan bahwa pembahasan soal pertanian bukan hal baru dalam tradisi Islam. Ia menyebut bahwa dalam beberapa riwayat, diskusi tentang pertanian bahkan disebut sebagai “sebaik-baik pembicaraan”, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan pentingnya memahami teks keagamaan bukan hanya dari sisi spiritual, tetapi juga sosial-ekologis. Maka pembacaan ulang hadis dalam konteks ketahanan pangan bukanlah upaya mengada-ada, tapi justru penggalian makna yang sudah lama tersimpan.
Di forum ini mahasiswa Sastra Arab membuktikan bahwa mereka mampu melampaui peran sebagai pembaca teks klasik. Mereka tampil sebagai penyambung tafsir yang mengaitkan ayat dengan realitas, hadis dengan isu lingkungan, maupun isu kontemporer lain. Hadis tidak lagi diposisikan dalam bingkai yang beku, melainkan dalam ruang hidup yang dinamis dan penuh persoalan melalui pembacaan yang kontekstual dan reflektif. “Swasembada dalam Sabda” membuktikan bahwa keilmuan berbasis humaniora tetap relevan dalam diskursus pembangunan. Sabda Nabi, jika dibaca dengan cermat, bukan hanya memberi inspirasi hidup dengan dimensi religi, tapi juga menjadi strategi menuju bangsa yang lebih mandiri.
Sebagai bagian dari keberlanjutan wacana yang telah dibuka dalam forum ini, dokumentasi lengkap Swasembada dalam Sabda telah disiarkan melalui kanal YouTube dan dapat diakses melalui tautan: uns.id/FGDketahananpangan. Melalui tayangan ini, diharapkan muncul ruang-ruang refleksi dan eksplorasi baru, baik dalam bentuk penulisan ilmiah, pengembangan riset interdisipliner, maupun pengayaan pendekatan humaniora dalam menjawab isu-isu strategis seperti ketahanan pangan. Lebih dari sekadar dokumentasi, forum ini diharapkan menjadi pemantik awal bagi kolaborasi lintas bidang yang menjadikan teks sebagai pijakan, dan realitas sebagai arah gerak keilmuan.
Penulis: Tim MBKM Program Studi Sastra Arab



